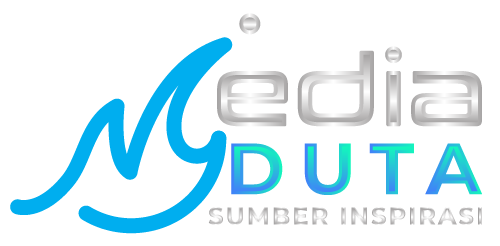Oleh : Syamsuddin – Yayasan Nurul Islam Insan Madani
“Manusia Indonesia itu kombinasi yang rumit antara sumber kekuatan moral (yaitu agama), sumber pembentukan kapasitas (yaitu ilmu pengetahuan) dan kesejahteraan”. Begitulah menurut kesimpulan Anis Matta -seorang cendekiawan dan pengamat geopolitik- tentang model manusia Indonesia. Kesejahteraan bermakna kebahagian. Bagi seorang muslim kebahagian itu tidak hanya terkait materi tetapi perpaduan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, kebahagian dunia dan akhirat. Kesejahteraan dalam arti yang komplit itu bersumber dari perpaduan yang apik antara kekuatan moral dan kapasitas yang besar.
Pemahaman dan pengamalan agama melahirkan akhlak, moral, dan karakter. Agamalah yang paling kuat membentuk moral sebab agama mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat kehidupan. Sungguh benar sabda Nabi Muhammad Saw, “Tidaklah saya diutus kecuali untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”. Hal yang patut disyukuri adalah kesadaran beragama yang semakin meningkat. Menurut penelitian dan realitas yang terlihat bahwa kesadaran beragama masyarakat semakin baik. Seseorang saat akan melakukan sesuatu seringkali bertanya tentang boleh atau tidak untuk dilakukan menurut agama. Dalam bidang pendidikan, kesadaran untuk menyekolahkan anak pada pendidikan Islam terus naik meskipun orang tua harus merogoh saku jauh lebih dalam. Keinginan untuk memiliki anak yang shalih, berakhlak, dan hafal al-Qur’an hampir terdengar dari semua orang tua muslim.
Hal yang perlu disadari, agama tidaklah bekerja sendiri. Agama (Islam) lebih banyak merupakan nilai dan prinsip kehidupan sehingga dapat berlaku abadi pada setiap zaman dan tempat. Karena lebih pada nilai, agama tidak menjangkau kepada hal-hal yang sangat teknis di luar ibadah khusus, terlebih dalam bidang sosial politik. Ilmu pengetahuanlah yang diserahi bidang teknis tersebut. Al-Qur’an menyebutkan, “Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui” Q.S. Al-Nahl: 43. Rasulullah Saw juga menegaskan “Kalian lebih tahu urusan dunia kalian”. Fakta yang menakjubkan, kata ilmu dan seakar kata dengannya disebutkan dan diulang dalam al-Qur’an sebanyak 854 kali. Tanpa butuh penjelasan tambahan, jumlah pengulangan ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan.
Ilmu sebagai sumber kapasitas. Kapasitas akan bertambah hanya bila pengetahuan terus mengalami penambahan. Pengetahuan berasal dari membaca dan pengalaman. Berhenti membaca berarti berhenti berpengetahuan. Pengalaman yang baik pun banyak didukung dari hasil membaca. Perkembangan kualitas tindakan, perkataan, dan keputusan seseorang banyak dipengaruhi oleh bacaannya. Bagitu juga kondisi pembicaraan masyarakat di dunia nyata dan media sosial menunjukkan penambahan pengetahuan atau tidak.
Perhatian agama yang sangat besar terhadap ilmu beserta sarananya (yaitu membaca) jauh tidak berimbang dengan kesadaran membaca kita. Berdasarkan data yang ada kondisinya sangat memprihatinkan. Pada tahun 2016 UNISCO pernah merilis tingkat literasi 61 negara yang menempatkan Indonesia pada peringkat 60. Selanjutnya, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2018 terkait kemampuan literasi (membaca, menulis, dan berhitung) siswa, Indonesia menempati urutan ke 71 dari 77 negara yang disurvei. Data ini membuat kita malu pada diri sendiri. Jarak antara kita dan ilmu pengetahuan masih terlalu jauh. Begitu pula hubungan kita dengan buku masih terlalu renggang.
Bidang yang paling memungkinkan untuk memulai meningkatkan kesadaran dan peningkatan kemampuan literasi adalah pendidikan. Saat ini hanya bidang pendidikan yang dianggap tempat yang paling baik untuk belajar dan meningkatkan kapasitas. Lebih sempit lagi hanya pada lingkup sekolah, perguruan tinggi, dan mungkin juga lembaga pelatihan. Lingkup lainnya itu untuk bekerja dan berkarir.
Tingkat perguruan tinggi adalah jenjang pengisian kapasitas yang sangat potensial. Saat itu seseorang memiliki fisik kuat, motivasi tinggi, kemampuan berpikir yang lebih mapan, dan waktu yang sangat luang. Namun peluang besar itu bukan berarti tidak memiliki tantangan. Masih banyak lulusan sekolah setingkat SMA yang tidak melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Selain itu, budaya literasi di perguruan tinggi juga semakin kering. Di sekitar kampus usaha kuliner begitu subur tetapi usaha buku mati, tak dapat tumbuh, dan tidak diminati. Di sebagian perguruan tinggi, tempat paling sepi adalah perpustakaan. Mahasiswa hanya datang berkunjung untuk menambah referensi skripsi atau tugas. Jangan tanya tentang berapa buku dibeli dan ditamatkan dalam satu tahun. Rendahnya literasi juga diperparah dengan sikap suka instan dan tidak jujur. Tingkat plagiasi cukup tinggi pada tugas-tugas akhir mahasiswa, sehingga harus diedit sedemikian rupa agar sesuai dengan ambang maksimal toleransi berdasarkan standar yang berlaku. Bahkan muncul layanan jasa pengerjaan makalah dan skripsi yang dijajakan secara online. Banyak sekali faktor yang melatarbelakangi kondisi ini salah satunya karena penumbuhan kesadaran literasi tidak dimulai sejak pendidikan dasar di sekolah.
Sekolah menjadi salah satu tempat dan sarana pendidikan utama selain keluarga, tempat ibadah, dan lingkungan. Demikian pula dalam pengembangan kemampuan literasi. Hanya sedikit orang tua yang tergolong visioner yang mampu membimbing sendiri anaknya untuk mengaji, menghafal, membaca, menulis, berhitung, serta berbicara menyampaikan gagasan; sebagian besar berharap banyak pada sekolah. Perubahan sosial masyarakat yang menuntut orang dewasa untuk fokus pekerjaan/karir semakin menambah beban bagi sekolah. Tempat ibadah (masjid) juga belum banyak mengambil peran dalam pengembangan kapasitas generasi penerus. Malah sebaliknya, bagi sebagian anak masjid merupakan tempat yang “galak” bagi mereka.
Tantangan tersebut menjadi tanggung jawab sekaligus peluang bagi sekolah, lebih khusus lagi bagi para guru. Sekolah harus berbenah guna mengambil peran besar dalam peningkatan kapasitas masyarakat lewat peserta didiknya. Tidak hanya menjadi tempat belajar membaca, menulis, dan berhitung; atau pada sekolah Islam ditambah belajar mengaji dan menghafal al-Qur’an. Diharapkan siswa tidak hanya mampu membaca tetapi menjadikan buku sebagai teman terbaik di kesendirian. Tidak hanya bisa menulis tetapi mampu menggoreskan perasaan dan pikirannya dalam sebuah karya tertentu. Tidak hanya mempu menghitung tetapi mampu menakar dan memprioritaskan sesuatu. Tidaknya hanya bisa membaca dan menghafal al-Qur’an tetapi menjadikan al-Qur’an petunjuk hidup bukan sekedar lantunan yang indah terdengar atau digelari hafidz (penghafal).
Sekolah melalui guru-gurunya dan semua pihak yang bertanggung jawab untuk menguras pikiran lebih dalam tentang bagaimana format peningkatan literasi di sekolah. Salah satu tantangannya, bagaimana menjadikan literasi menjadi bagian dari budaya sekolah. Menjadikan buku bagi siswa bagian dari aktivitas kehidupannya seperti halnya mainan. Usaha-usaha untuk mencapai gambaran tersebut sebaiknya tidak hanya diperoleh dari meniru sekolah lain tetapi merancang secara mandiri dengan berbagai referensi yang ada. Sebab terlalu banyak meniru dapat mematikan kreativitas dan tidak optimalnya usaha.
Tulang punggung dari usaha penumbuhan dan pengembangan literasi adalah guru. Dan yang paling awal yang perlu dibenahi oleh guru dalam hal ini adalah pribadi masing-masing. Sebelum beranjak pada usaha di lapangan sisi, pemikiran perlu menjadi perhatian. Guru harus menjadi pribadi-pribadi yang berjiwa dan berpikiran besar. Di antara pemikiran yang perlu dimiliki: pertama, cita-cita peradaban. Kesadaran tentang cita-cita besar untuk menjadi bangsa yang besar dan umat terbaik dalam realitas. Kesadaran diri bahwa ia bagian dari bangsa dan umat. Berusaha meningkatkan kapasitas guna kontribusi pada cita-cita yang tinggi tersebut. Termasuk meningkatan kemampuan dan membentuk kebiasaan membaca buku sebab semangat belajar haram hilang dari seorang guru. Jika melihat karya tulis ulama terdahulu yang begitu banyak dan tebal dengan alat tulis belum secanggih sekarang, dapat tergambar bagaimana kuat budaya membaca masyarakatnya baik dari kalangan awam terlebih para ulama. Kedua, mengajar dan menjalankan berbagai tugas sebagai guru dengan kesadaran akan tanggung jawab sejarah (mas’uliyah tarikhiyah). Hasil jarih payah guru saat ini akan dituai pada generasi yang sedang dididiknya. Ketiga, menikmati peran sebagai guru. Mengajar, membimbing, mengarahkan, memotivasi, membiasakan, dan membudayakan siswa adalah jihad bagi seorang guru. Jihad itu memfokuskan pikiran, memaksimalkan usaha, dan mengarahkan perasaan untuk suatu cita-cita dengan mengharapkan keridoan pada Tuhan yang tidak pernah lalai membalas kebaikan hamba-Nya. Keempat, sabar dan istiqomah.
Setelah selesai dengan urusan pribadi guru, barulah pada usaha membangun sistem pengembangan literasi, melakukan pemetaan kemampuan dan sarana pendukung yang mampu diupayakan, menetapkan capaian, dan menyusun program. Memulai dengan perencanaan yang cukup, proses yang terintegrasi, evaluasi dan perbaikan yang berkesinambungan. Semua itu perlu dilakukan dengan kerjasama yang baik dan semangat kolaborasi yang solid.
Demikianlah, manusia Indonesia yang shalih (bermoral), alim (berpengetahuan), dan makmur sebagai ide dalam bidang pendidikan. Peningkatan literasi sebagai usaha utama dalam pemenuhan pada sisi kapasitas pengetahuan. Dan guru adalah aktor utama yang menjalankan pengembangan literasi di sekolah. (*/dirman)